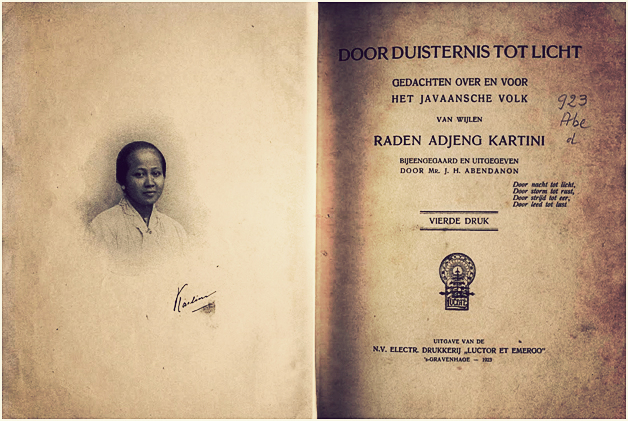Hijau dan kuning keemasan. Kedua warna itu berulang kali menyapa saat kami dipandu mengelilingi Museum Kartini di Rembang. Bangunan tua ini dahulu merupakan rumah dinas para bupati Rembang selama satu setengah abad, termasuk ketika Adipati Djojoadhiningrat, suami Kartini, menjabat sebagai bupati di sana. Saat dialihfungsikan menjadi museum pada tahun 2004, semua pintu dan jendela di kompleks bangunan dan paviliun seluas dua hektar tersebut kembali dicat dengan warna hijau tua dan hiasan ukiran kuning keemasan seperti semasa Kartini tinggal di sana.
Kedua warna tersebut mendominasi kamar tidur Kartini, tempat tur keliling museum kami dimulai. Kamar ini, ruang pribadi Kartini semasa menjadi istri dan seorang calon ibu, kini disebut sebagai Ruang Pengabadian R.A. Kartini. Kami menengok beberapa benda peninggalannya di kamar itu. Meja rias mungil di pojok ruangan, kebaya beludru berwarna biru tua dengan potongan sederhana yang dikenakannya dalam upacara pernikahan, serta tempat tidur yang juga menjadi tempat ia menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Kedua warna tersebut kembali menyapa saat kami mengakhiri tur di beranda tempat Kartini sering menghabiskan waktu sore harinya. Saat itu angin sore berhembus meniup rumput tinggi dan bunga-bunga kuning di taman itu sehingga mereka tampak seperti menari-nari kecil. Beranda ini tampak seperti sebuah tempat yang menyenangkan untuk membaca, menulis, berpikir, atau sekadar merenung saja. Ini sudut yang terkesan jauh lebih ramah dibandingkan bagian lain dari rumah sang suami yang dipenuhi perabot yang mewah dan serius. Kami bisa membayangkan, di sinilah ia menuliskan banyak surat-suratnya yang terkenal itu.
“Taman ini dinamakan Taman Inspirasi, “kata Ibu Penjaga Museum. “Di sinilah Kartini banyak mendapat inspirasi. Tidak hanya untuk menulis, namun juga melukis, menggambar pola batik, dan bermain piano.”
Saya kemudian bertanya mengenai barisan kamar-kamar berukuran kecil yang berjajar tepat di seberang beranda itu. “Oh, itu adalah kamar para garwo ampil. Pak Djojo punya tiga orang istri lain.” Ibu penjaga menyampaikan informasi itu dengan nada yang biasa saja. Mungkin karena sudah demikian jamak bagi pria bangsawan Jawa masa itu untuk memiliki banyak istri. Sementara saya, di sisi lain, tetap terkesiap mendengarnya. Setiap kali Kartini berada di beranda yang memebri banyak inspirasi itu, ia akan memandang tepat ke ruangan seberang tempat perempuan-perempuan lain dalam hidup suaminya berada.
Pernikahan Kartini selalu mengundang tanda tanya untuk saya. Saat berada di bangku sekolah menengah saya mengetahui bahwa Kartini menikah dengan Bupati Rembang yang berusia dua kali dirinya dan telah memiliki tiga orang istri. Saat itu saya menganggap Kartini telah mengkompromikan cita-citanya. Saya menganggap ia telah menyerah. Namun bersama usia yang bertambah dewasa dan dan bacaan mengenai Kartini yang bertambah banyak, hal-hal terasa lebih rumit.
Adipati Djojoadhiningrat, yang oleh Ibu penjaga museum disebut dengan panggilan Pak Djojo, melamar Kartini atas permintaan almarhum Garwo Padmi-nya (istri pertama) sebelum meninggal dunia. Sang Garwo Padmi rupanya telah mendengar dan mengagumi sosok Kartini dari Jepara dan berpikir bahwa ia adalah jodoh yang pantas untuk suaminya. Kartini meminta waktu tiga hari untuk menimbang lamaran ini. Dalam waktu itu ia mencari segala informasi mengenai Pak Djojo. Ia menemukan bahwa Pak Djojo memiliki pendidikan tinggi, walaupun tidak sampai lulus dari jurusan pertanian di Wageningen, Belanda. Ia pun mendengar bahwa Pak Djojo adalah Bupati Rembang yang handal. Saat itu Kartini telah berusia 24 tahun, ia dianggap telah melewati masanya bagi perempuan untuk menikah. Penolakannya akan berbagai lamaran pernikahan kerap menimbulkan pergunjingan yang mengganggu ayah Kartini yang mulai sakit-sakitan. Ayah yang begitu ia cintai.
Pak Djojo dianggap Kartini sebagai yang terbaik diantara pelamar lain, karenanya diakhir hari ketiga ia menyanggupi lamarannya dengan beberapa persyaratan. Sang calon suami harus mendukungnya dalam mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi di Rembang. Kartini juga akan membawa pengrajin-pengrajin handal Jepara untuk mengembangkan industri ukir. Kartini juga hanya akan berbicara dalam bahasa Jawa ngoko kepada suaminya dan bukan dalam bahasa Kromo Inggil yang begitu formal. Dan terakhir, permintaannya yang paling kontroversial untuk adat saat itu, adalah bahwa dalam upacara pernikahan ia tidak akan melakukan upacara berjalan jongkok, berlutut, dan menyembah kaki mempelai pria.
Pak Djojo menyanggupi semua persyaratan Kartini, bahkan menyatakan kesediaannya menceraikan semua Garwo Ampil-nya demi Kartini. Kartini menolak tawaran itu. Ia mengerti betapa perceraian akan menempatkan sang perempuan dan juga anak-anaknya dalam posisi ekonomi dan sosial yang lemah. Dan menikahlah mereka. Kartini mengenakan sebuah kepaya beludru biru gelap yang sederhana sebagai pakaian pengantinnya. Kebaya yang saat ini dipamerkan di Museum Kartini di Rembang.
“Aku tahu bahwa saat itu sangat wajar seorang bangsawan memiliki banyak istri. Namun mengingat betapa keras Kartini menyuarakan penolakannya pada poligami, apakah kalian pikir Kartini bahagia dalam pernikahannya? “ tanya saya pada kawan-kawan perjalanan.
Fani mengangguk-anggukan kepalanya, “Hmmm… ada bukti-bukti yang menunjukkan begitu. Surat-surat terakhirnya berkisah betapa ia menikmati merawat anak-anak suaminya, mendongeng untuk mereka sambil minum teh bersama sang suami. Mereka berdua pun tampaknya cukup cocok. Keduanya menyukai karya seni Jawa dan ingin mempromosikannya ke Belanda, Ibu Penjaga Museum pun mengatakan Pak Djojo pun sangat mendukung cita-cita Kartini mendirikan sekolah untuk perempuan-perempuan pribumi. Ia memberikan Kartini sebuah paviliun yang digunakannya sebagai sekolah tempat ia mengajar.”
Indah mendongak dari buku yang ia baca, ““Suamiku tidak hanya suami bagi saya. Ia juga kawanku sejiwa”, begitu ia menulis kepada Profesor Anton, seorang kawan lama keluarganya. Sepertinya Kartini memang mencintai suaminya.”
“Tapi ingatkah kalian akan surat Kartini kepada Nyonya Abendanon saat ia menemukan dirinya hamil? Walau ia bahagia akan kehamilannya, ia menulis bahwa seandainya bayinya perempuan, ia berharap sang anak tidak akan dipaksa menjalankan hal-hal di luar cita-citanya. Ia secara eksplisit menulis bahwa ia berharap sang suami akan akan selalu mendukung anak perempuannya, bahkan mengijinkan seandainya sang anak tidak ingin menikah sama sekali. Kurasa ia sedang bicara mengenai kesedihannya sendiri juga, kesedihan yang belum tuntas,” Afra menyampaikan sudut pandang yang lain.
“Ingatkah kalian, Ibu Penjaga Museum berkata bahwa sekolahnya ditutup dan tidak pernah dihidupkan lagi segera setelah Kartini meninggal?” Twosocks ikut berpendapat. “Sekolah di Rembang hanya berdiri selama delapan bulan saja. Jika Pak Djojo benar-benar mencintai Kartini, tentu ia akan berusaha untuk tetap meneruskan sekolah itu sebagai sesuatu yang begitu didamba mendiang istrinya?”
Tak satu pun dari kami berbicara lagi. Kami semua sibuk dengan pikiran masing-masing. Tur Kartini membawa kami lebih mengenal sosok Kartini, namun semakin kami menelusuri langkahnya dan mengerti akan situasi yang dihadapinya, semakin kami menemukan misteri-misteri yang tak terjawab. Apakah Kartini benar-benar mencintai suaminya seperti konsep cinta yang kami ketahui sekarang? Apakah Kartini mencintai sang suami hanya sebagai bentuk penerimaannya akan situasi yang dihadapinya? Apakah ia jatuh cinta secara seketika atau setahap demi setahap? Apakah ia benar-benar bahagia di Rembang dalam pernikahan yang tidak benar-benar diinginkannya?
Mungkin kami tidak akan pernah benar-benar tahu.
Gypsytoes
Catatan ini adalah artikel keenam dari Seri Tur Kartini, inisiatif kolaborasi The Dusty Sneakers dan Pamflet, organisasi anak muda yang berbasis di Jakarta, untuk mengenal sosok dan pemikiran Kartini lebih jauh dengan melakukan perjalanan ke Jepara dan Rembang. Kumpulan catatan perjalanan Tur Kartini dapat diunduh di sini.