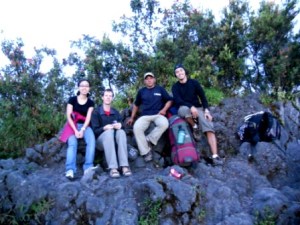Hampir setahun sejak saya dan Gypsytoes bertualang sendiri-sendiri. Ia berjalan dan menari di pojok-pojok Eropa yang eksotis sementara saya melihat matahari terbit di sudut-sudut Indonesia yang masih selalu memberi kejutan. Namun pada sore yang sejuk di awal bulan Agustus, kami bertemu kembali di sebuah tempat di selatan India. Gypsytoes tampak berdiri menunggu saat saya keluar dari terminal Bengaluru airport. Dengan rok selutut, anak ini tampak manis. Wajahnya pun terlihat sedikit lebih dewasa sejak terakhir saya melihatnya. Sungguh kami kegirangan bisa bertemu kembali. Kami berpelukan sampai berputar-putar segala. Sepuluh hari di awal Agustus itu, di Bangelore India, kami kembali berjalan bersama.
Bangalore adalah salah satu kota metropolis utama India dan sebagai kota eksportir utama produk IT ia disebut the Silicon Valley of India. Namun jangan lantas terbayang sebuah kota ultra modern dengan fasilitas dan penampilan yang mutakhir. Berjalan di sebagian besar jalanan utamanya membuat kami ditarik ke sebuah era di akhir tahun tujuh puluhan. Para pria berjalan dengan kemeja dan celana ciut brai seperti Roy Marten dalam film ‘Romantika Remaja’, iklan-iklan di jalanan mengingatkan kami pada iklan pepsodent jaman sekolah dasar dahulu, dan tata tamannya akan membuat orangtua kami teringat masa muda saat mereka berpacaran. Seperti halnya setiap perjalanan, maka tempat baru, orang-rang baru, kebudayaan baru, selalu adalah hal yang luar biasa menarik. Bangalore memiliki sejarah kebudayaan berabad-abad, salah satu pusat tari dan musik klasik India, rumah dari banyak pemikir India dan segudang intelektual muda. Di kota yang sejuk ini, setiap hari adalah petualangan yang menyenangkan.
Seperti yang pernah saya katakan, berbicara dengan Gypsytoes selalu menjadi bagian terbaik dari setiap perjalanan dengannya. Setiap hari kami berjalan menyusuri jalanan Bangalore dan tak henti bicara-bicara. Mengenai petualangan-petualangannya setahun terakhir, soal-soal yang terjadi di tanah air, riset yang sedang dilakukannya di India, juga hal-hal intim mengenai orang-orang yang kami sayangi, atau sekedar hal-hal ganjil yang terjadi pada Arip. Kami mengobrol sambil minum teh yang luar biasa di infinitea di Cunningham Road, di sepanjang Church Street yang padat, di antara buku-buku murah yang memabukkan di Blossom Book House, di bangku taman yang rindang di Lalbagh, atau sekedar obrolan ringan sambil sarapan saat kami sama-sama belum mandi. Bangalore yang juga memiliki sebutan City of Gardens memang selalu memberikan ruang untuk mereka yang senang untuk duduk, berbicara, atau melamun. Diantara jalanannya yang padat berhimpit, taman-taman kota tersebar di sana. Dua yang terbesar adalah Lalbagh dan Cubbon Park. Setiap hari kita akan melihat sekumpulan orang yang bercengkerama, perempuan dengan saree yang anggun bersama pasangannya yang dimabuk cinta, tuna wima yang tertidur, atau orang tua yang sekedar menyendiri melamun. Kami bahkan mengunjungi Brindavan Garden,sebuah taman di Mysore, kota tetangga Bangalore. Taman yang hijau luas dengan tata letak yang indah. Taman ini mengingatkan kami pada film-film romantis Bolywood, di mana pasangan yang jatuh cinta menari dan menyanyi di antara pohon taman yang rindang, air mancur, dan bunga yang bermekaran. Sungguh menyenangkan duduk di bangkunya sambil minum masala chai, teh kayu manis khas India.
Dan tentunya, setiap kota di India termasuk Bangalore dipenuhi kuil-kuil Hindu. Pura Siwa di Shiv Mandir dengan patung Siwa nya yang menjulang sampai pura-pura kecil semacam Muthyalamma Temple. Sungguh menyenangkan untuk memperhatikan mereka yang mempraktekkan Hindu dengan cara yang khas dan berbeda dari di mana saya berasal. Bentuk bangunan, pakaian, atau tata pemujaannya. Pendeta di Muthyalamma pun tampak senang melihat saya yang datang dari jauh. Ia berkata bahwa ini pasti buah karya para Dewa atau semacamnya lalu mengundang saya berdoa di sana. Saya bahkan diberkati dengan tanda merah di jidat. Kami sempat pula mengunjungi Iskon Temple yang megah. Ada sedikit kejadian lucu di kuil para penganut Hare Krishna ini. Saat itu para peziarah cukup banyak dan kami terhimpit dalam sebuah antrian menaiki tangga ke tempat pemujaan utama. Yang kemudian baru kami sadari adalah bahwa kami harus melafalkan doa Hare Krishna di setiap ubin dan anak tangga yang kami injak. Kami tidak bisa mundur lagi dan mau tidak mau harus berjalan perlahan bersama kerumunan dan melafalkan doa tersebut.
Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare hare. Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Benar-benar di setiap ubin! Tidak kurang dari tiga puluh menit dan tidak kurang satu ubinpun! Untuk beberapa hari ke depannya doa itu terus terngiang di kepala kami.
Bangalore juga rumah bagi mereka yang berkesenian. Salah satu yang sangat berkesan adalah Ranga Shankara, sebuah komplek kesenian semacam Salihara di Pasar Minggu. Tempat pertunjukan teater ini memiliki filosofi a play a day, artinya sepanjang tahun kita akan melihat lebih dari 300 pertunjukan! Hebat sekali. Mereka bahkan punya panggung teater untuk anak-anak. Kami sempat menonton pertunjukan berjudul Ms Meena, kisah aktris terkenal india yang pulang ke kampungnya yang melarat. Kami langsung menempatkannya sebagai salah satu pertunjukan teater favorit kami. Pertunjukannya dipenuhi gerak tari dan lagu yang ekspresif, kisah yang kuat, percakapan yang lucu, dan twist yang mencengangkan diakhir. Walaupun disampaikan dalam bahasa Inggris, tentunya beberapa kali adegan juga diselingi dengan lelucon dalam bahasa lokal. Saat itu kami hanya akan berpandangan linglung melihat orang-orang India yang tertawa kegirangan di sekitar kami.
Sepuluh hari saya menghabiskan waktu bersama Gypsytoes di Bangalore. Setelah hampir setahun berpisah, sepuluh hari itu kami kembali berjalan, menari, dan berbicara tanpa henti. Semua seperti terasa normal kembali. Beruntunglah mereka yang memiliki sahabat terdekatnya, yang sama sekali tidak terasa asing saat bertemu kembali setelah lama berpisah. Gypytoes masih anak yang bersemangat, lucu, dan pintar. Pada saat yang bersamaan ia pun masih tersandung di tangga atau mual di perjalanan bus malam dari Mysore ke Bangalore. Dari India saya kembali ke Jakarta sementara Gypsytoes pergi ke Taipei untuk sebuah urusan sebelum kembali ke Belanda. Namun empat bulan dari sekarang sahabat saya ini akan pulang ke Indonesia. Kali ini untuk menetap. Saat itu, di bulan Desember dimana Jakarta selalu tampak lebih indah, kami akan berjalan bersama lagi.
Agustus 2010, Twosocks